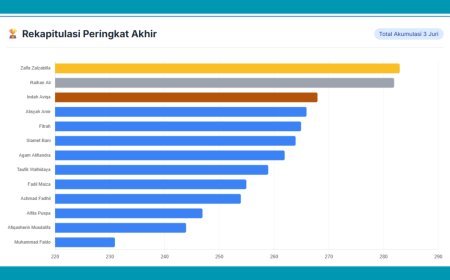Api Perjuangan dari Tanah Merdeka
Sejarah Resolusi Jihad NU 1945

Aroma kemerdekaan yang baru dihirup pada 17 Agustus 1945 berpadu dengan ketegangan yang menyesakkan. Di Jawa Timur, khususnya Surabaya, Proklamasi menciptakan kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh gelora nasionalisme yang menyala. Kota Pahlawan itu langsung menjadi pusat nadi revolusi. Untuk mempertahankan kedaulatan, mobilisasi rakyat terjadi secara masif. Angka-angka membuktikan kesiapan mereka: diperkirakan 20.000 pasukan TKR datang dari berbagai penjuru, didukung oleh sekitar 140.000 rakyat pejuang yang siap mengorbankan jiwa raga.
Namun, harapan itu lekas dihantam kenyataan pahit. Situasi genting di Surabaya mencapai titik didih dengan kedatangan pasukan Sekutu (AFNEI) di Tanjung Perak pada 25 Oktober 1945. Misi resmi mereka hanyalah melucuti tentara Jepang. Tapi, di balik seragam Sekutu, tersembunyi niat busuk: NICA (Netherlands Indies Civil Administration), atau Belanda, telah memboncengi mereka.
Di dermaga Tanjung Perak, seorang pejuang muda menatap kapal-kapal Inggris yang merapat. Ia berbisik kepada rekannya: “Mereka bilang Inggris tidak melibatkan NICA, tapi lihatlah, seragam Belanda itu nyata! Kita dikhianati.” Rakyat merasakan pengkhianatan mendalam. Kekhawatiran akan kembalinya penjajahan membakar amarah, terutama mengingat Belanda telah menorehkan sejarah kekejaman yang mengancam ketenteraman umum.

Jauh sebelum Jenderal Mallaby tiba, Surabaya sudah menentukan sikapnya. Pada 19 September 1945, di Hotel Yamato yang angkuh, sekelompok pemuda berani mengepung hotel, menuntut bendera Belanda diturunkan. Massa berteriak: “Turunkan bendera tirani itu! Ini bukan lagi tanah jajahan! Kami sudah merdeka!” Kemudian, tangan-tangan pemuda merobek warna biru, mencabutnya paksa, dan mengerek bendera Merah Putih yang suci. Peristiwa yang menewaskan Mr. Ploegman ini adalah deklarasi perang sipil: kedaulatan tidak bisa ditawar.
Di tengah krisis yang mengancam ini, Pemerintah Pusat di Jakarta seolah membeku, cenderung mencari penyelesaian diplomatik. Sementara itu, medan tempur di Surabaya sudah berlumuran darah. Ketiadaan komando yang jelas dari pusat menciptakan kekosongan moral. Para ulama merasa terpanggil untuk bertindak cepat, menyadari bahwa jika negara baru ini runtuh, eksistensi umat Islam dan pelaksanaan ajaran agama akan terancam.
Maka, upaya mempertahankan dan menegakkan negara merdeka menurut hukum agama Islam dilihat sebagai sebuah kewajiban suci. Mata dan hati umat tertuju pada Tebuireng, pada Hadratussyekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Pengaruh besar beliau menjadikan setiap fatwa yang dikeluarkannya memiliki otoritas mutlak.
Merasa terpanggil oleh kondisi darurat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengambil inisiatif strategis. Beliau memanggil kiai-kiai utama, termasuk KH Abdul Wahab Hasbullah, untuk mengumpulkan perwakilan NU dari seluruh Jawa dan Madura.
Pada 21 Oktober 1945, musyawarah darurat diselenggarakan di sebuah rumah sederhana di Kampung Bubutan VI Nomor 2, Surabaya. Rapat yang dipimpin oleh KH Abdul Wahab Hasbullah ini berlangsung intensif selama sehari semalam.
KH Abdul Wahab Hasbullah membuka pertemuan dengan suara tegas: “Kita berkumpul di sini untuk menentukan sikap kolektif umat Islam dalam menghadapi Belanda yang memboncengi Sekutu. Tujuan kita adalah mendesak pemerintah dan menyatakan sikap kita! Ini bukan lagi soal politik semata.”
Pada malam 22 Oktober 1945, lahirlah keputusan suci yang mengguncang dunia: "Resolusi Jihad Fii Sabillilah."
Naskah Resolusi Jihad merupakan dokumen teologis-politis fundamental, sebuah ijtihad kebangsaan:
- Menimbang: Bahwa mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum AGAMA ISLAM, termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam.
- Memutuskan: Memohon dengan sangat kepada Pemerintah RI agar menentukan suatu sikap, dan supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat "sabilillah" (perang di jalan Allah) untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka.
Penetapan status hukum Resolusi Jihad merupakan kunci efektivitas mobilisasi. Ulama menetapkan bahwa mempertahankan negara adalah Fardhu Ain—kewajiban individu yang harus dikerjakan oleh setiap individu Muslim.
Seorang Kiai menegaskan: “Kewajiban berjihad ini berlaku bagi mereka yang berada dalam jarak lingkaran 94 km—setara dengan dua marhalah atau jarak tempuh perjalanan sehari semalam—dari tempat masuk dan kedudukan musuh! Dalam radius ini, berjuang adalah keharusan, bukan pilihan.”
Fatwa ini secara teologis meniadakan pilihan untuk abstain. Konsensus serupa juga muncul dalam Moe'tamar Oemmat Islam Indonesia di Jogjakarta pada 7–8 November 1945, yang juga memutuskan untuk memperkuat persiapan umat Islam untuk berdjihad fi Sabilillah.

Begitu Resolusi Jihad dideklarasikan, ia meledak menjadi mobilisasi fisik. Jaringan pesantren NU bertransformasi menjadi markas komando revolusi. Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah segera terbentuk. Sosok K.H. Masykur, pendiri PETA, menjabat sebagai komandan tertinggi Barisan Sabilillah. Laskar santri yang bertempur di bawah semangat sabilillah memiliki modal utama berupa keberanian spiritual yang tinggi. Didorong keyakinan bahwa kematian adalah syahid, para pejuang ini tidak gentar menghadapi musuh yang superior.
Resolusi Jihad adalah sumbu yang menyulut perlawanan total. Ketika gencatan senjata yang rapuh disepakati pada 30 Oktober 1945 antara Inggris (diwakili Jenderal Mallaby) dan pihak Surabaya (Gubernur Soeryo), harapan damai segera hancur lebur oleh insiden yang mengubah segalanya: kematian Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby pada hari yang sama.
Kematian Mallaby memicu kemarahan Inggris. Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh, pengganti Mallaby, mengeluarkan ultimatum yang menghina pada 9 November 1945, menuntut penyerahan tanpa syarat.
Namun, di telinga para pejuang yang telah bersumpah Fardhu Ain, ultimatum itu tak lebih dari gemerisik kertas. Di markas Barisan Sabilillah, K.H. Masykur mengumpulkan pasukannya.
K.H. Masykur berkata: “Inggris menuntut penyerahan tanpa syarat? Komando kita adalah No Surrender! Kita sudah disumpah berjuang fardhu ain. Kematian kita adalah syahid. Rasa takut tidak boleh lebih besar dari janji Allah!”
Pada 10 November 1945, Pertempuran Surabaya meletus. Resolusi Jihad adalah faktor moral krusial yang mengubah pertempuran ini menjadi Perang Sabil. Laskar Hizbullah dan Sabilillah bertempur bahu-membahu, menjadikan Surabaya simbol perlawanan total.

Resolusi Jihad menghasilkan Nasionalisme Jihad, prinsip yang mengukuhkan bahwa mempertahankan NKRI adalah prasyarat mutlak bagi umat Islam untuk dapat menjalankan agamanya secara sempurna. Para sejarawan, termasuk Martin van Bruinessen, menegaskan bahwa Resolusi Jihad NU adalah mata air spiritual yang menghasilkan Pertempuran Surabaya.
Warisan abadi ini diakui negara. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional (HSN) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo merupakan pengakuan resmi negara terhadap kontribusi historis kaum santri. Melalui Resolusi Jihad, makna 'santri' bertransformasi menjadi identitas kolektif para pejuang yang mendasari semangat Merah Putih dengan nilai-nilai spiritual.
What's Your Reaction?
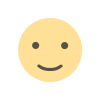 Like
0
Like
0
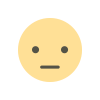 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
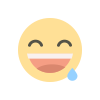 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
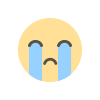 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0